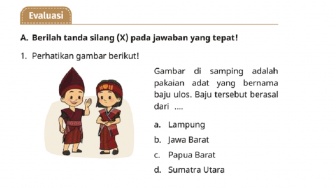- Puputan Badung (20/9/1906) adalah pilihan martabat, bukan bunuh diri, lahir dari tabrakan hukum dua budaya.
- Kabar Puputan Denpasar memicu "Baliseering", upaya pelestarian Bali yang dikendalikan, mengubah sejarah jadi citra.
- Memahami Puputan kini butuh kejujuran, menolak romantisasi atau sinisme, agar masa lalu bicara apa adanya.
SuaraBali.id - Artikel opini ditulis sebagai peringatan Puputan Badung 20 September 1905 oleh Ulin Yusron, pegiat seni budaya tinggal di Bali, lulusan UNS, IKJ dan ISI Bali
Pagi di Lapangan Puputan selalu mulai dari hal-hal kecil. Rumput lembap, anak-anak yang mengejar bayang layangan, derit gerobak es yang lewat pelan. Patung itu membeku seperti nada yang ditahan, seolah meminta kita menurunkan suara sebelum menyebut 1906. Menulis tentang puputan bukan untuk mengundang tangis, bukan untuk menyalakan amarah—melainkan memberi tempat bagi ketepatan: agar keindahan Bali tak hanya berdiri di panggung tari, tetapi juga di atas kejujuran yang tidak memuja kematian dan tidak mengharuskan memaafkan peluru. Ketepatan itu tidak lahir dari retorika; ia lahir dari tanggal, dari jarak, dari orang-orang yang pernah berdiri di lapangan ini sebelum patung menjadi patung.
Di pesisir selatan, berabad lamanya, ada hukum yang menyebut tawan karang—hak penguasa pantai untuk menyita kapal karam beserta muatannya, sebagai kompensasi atas upaya penyelamatan sekaligus pernyataan kedaulatan. Di meja Batavia, hukum yang sama dibaca sebagai perompakan—noda pada arteri dagang dan wibawa Eropa. Dua dunia yang sama-sama yakin pada kebenarannya berpapasan tanpa juru bahasa.
Ketika I Gusti Ngurah Made Agung naik takhta (1902), ia menolak kompromi yang dianggap menggerus martabat puri: di satu horizon, “hak”; di horizon lain, “pelanggaran”. Sejarah jarang mau menjadi penengah—ia lebih sering menjadi panggung ketika dua logika saling meniadakan.
Baca Juga:Lokasi yang Dulu Angker Jadi Tempat Persembuyian Para Rampok Kini Tambang Dolar di Bali
Kalimat pembuka ekspedisi itu ditulis oleh karamnya sebuah kapal dagang, Sri Kumala, di Sanur (27 Mei 1904). Dari sengketa muatan dan ganti rugi, kata-kata cepat berpindah menjadi alasan untuk menegakkan “ketertiban”. Ultimatum dikirim, perwira menghitung logistik, dan pada 14 September 1906 pasukan mendarat di Sanur.
Artileri mengukur jarak sebelum mengukur makna. Gerak maju ke Kesiman dan Denpasar tidak hanya menang atas benteng; ia juga menang atas ritme—perang modern selalu menguasai tempo lebih dulu.
Lalu 20 September 1906, Denpasar berubah menjadi ruang di mana dua pengertian tentang kehormatan saling berhadapan. Dari Puri Denpasar dan Puri Pemecutan, orang-orang berjalan dalam putih, keris di pinggang, langkah seperti upacara. Saksi mata dari rombongan penakluk mencatat adegan yang “tak masuk akal militer”: perhiasan dilemparkan ke arah serdadu; perempuan berdiri sejajar, wajah datar di depan laras. Di buku si pemenang, itu dicatat sebagai “bunuh diri massal”—kata yang rapi, sekaligus gagal.
Sebab bagi mereka yang melangkah, itu bukan kultus pada maut, melainkan keputusan menutup kalimat dengan tanda baca yang dipilih sendiri: puputan—habis-habisan. Kehormatan pada hari itu bukan abstraksi; ia adalah gerak tubuh, pilihan yang sadar atas harga diri di hadapan logika yang menafsirkan adat sebagai kriminalitas.
Siapa menembak duluan? Sumber kolonial cenderung menyebut peluru pertama datang dari pihak Bali; riwayat lokal menaruh tanda tanya pada detik-detik terakhir yang dorong-tarik, pada provokasi yang tak lagi jernih ketika jarak tinggal hitungan langkah. Tapi bahkan jika peluru pertama bisa ditetapkan secara forensik, pertanyaan itu tak cukup menafsirkan apa yang terjadi di lapangan: dua dunia hukum bertubrukan, dan keduanya memakai kosakata yang saling meniadakan.
Baca Juga:Datang Tak Diundang ke Acara Orang, Buruh Serabutan Ini Rudapaksa Bule Kanada
Setelah itu, sejarah bergerak cepat: Tabanan jatuh pada akhir September; struktur kekuasaan dirombak; benda, tanah, dan naskah berpindah tangan. Kalimat “ketertiban dipulihkan” muncul di laporan—frasa yang selalu berhasil merapikan puing dalam satu baris.
Namun debu yang baru saja reda itu tak mampu menutup bau besi. Kabar tentang darah di Denpasar menyobek jubah moral Politik Etis di negeri jauh. Maka luka didandani dengan bahasa pelestarian. Sejak 1910-an lahir gagasan yang kelak kita sebut Baliseering: Bali dijaga agar “asli”, modernisasi ditahan, adat dibekukan seperti bunga di dalam kaca.
Asal katanya terasa penuh kasih; cara bekerjanya adalah kontrol. Museum Bali dibuka (1932), mengumpulkan benda-benda yang sebagian lahir dari penaklukan dan pengumpulan paksa; di balik kaca, puputan yang semula sebuah keputusan akhir diubah menjadi citra yang bisa ditatap tanpa rasa bersalah. Brosur pariwisata pun menjadi mahir: Pulau Dewata, surga timur terakhir—romantisme yang paradoksnya tumbuh dari sepotong hari yang mengerikan.
Satu abad lebih berlalu. Sore di Lapangan Puputan hari ini adalah ritme yang kita kenal: pedagang berkemas, pegawai bergegas, turis memotret patung dengan senyum yang kaku. Tempat ini, seperti banyak lapangan lain, hidup dari kegunaan sehari-hari; namun ia juga menyimpan tugas yang lebih sunyi: mengembalikan wajah kita sendiri. Sebab ingatan bukan monumen—ia adalah tata bahasa. Kita mudah mengatakan “heroik”, sama mudahnya kita mengucap “tragik”.
Puputan meminta kita menahan keduanya dalam satu napas: keputusan yang sekaligus luhur dan fatal. Ia menjaga martabat komunitas, tetapi juga memanggil maut. Menjadi jujur pada 1906 berarti menolak dua kemudahan: romantisasi yang membuat kita nyaman, dan sinisme yang membuat kita merasa lebih cerdas daripada para pendahulu.
Barangkali di situlah gunanya menyebut tanggal, menyebut nama, menyebut urut-urutan: Sri Kumala karam (27/5/1904); pendaratan Sanur (14/9/1906); dua prosesi putih di Denpasar (20/9/1906); Tabanan meregang pada akhir bulan yang sama. Menyebut tawan karang, bukan untuk membenarkan, melainkan untuk menempatkan; menyebut Baliseering, bukan untuk menuduh, melainkan untuk membongkar bagaimana cinta pada “keaslian” bisa bekerja sebagai kurung.